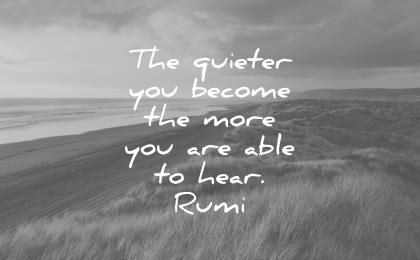ASWAJADEWATA.COM |
Oleh: Muhammad Rodlin Billah (Gus Oding)
Ternyata apa yang menjadi tujuan kami menemui saudara-saudara kami di kota sebelah hari ini tetiba menjadi jelas justru setelah acara selesai:
Hati saya berteriak keras sebab tak siap atas pengajaran dari Allah SWT melalui seorang yang tidak kami kenal sebelumnya dan tidak kami duga.—–
Ceritanya sesaat sebelum kami pulang kembali menuju kota tempat kami tinggal, sambil menunggu kereta kami yang terlambat sekitar satu jam, kami dipertemukan kembali dengan seseorang yang juga hadir pada acara di masjid kota ini tadi siang sebagai seorang hadirin.
Wajahnya cerah. Senyumnya senantiasa tersungging. Dari penampakan fisiknya ia jelas bukanlah orang Indonesia. Ia lebih tampak seperti seorang Eropa, namun ia dapat berbahasa Indonesia dengan baik.
Setidaknya ini tercermin saat ia menyampaikan bila hampir keseluruhan isi dari mauidhoh hasanah di masjid tadi siang sekitar biografi Ibnu Athoillah As-Sakandari serta magnum opusnya Al-Hikam ia mengerti dengan baik.
Dalam pertemuan yang hanya sekitar 5 menit itu ia menceritakan bila telah mengunjungi banyak habib, diantaranya termasuk Habib Luthfi bin Yahya Pekalongan. Ia bahkan sempat menetap di Jakarta selama dua tahun atas permintaan Habib Muchsin Jakarta.
Saya bersama istri mencermati dengan takjub ceritanya. Saat itu juga saya sampaikan betapa ia adalah orang yang beruntung, sedangkan kami yang asli Indonesia saja belum berkesempatan bertemu apalagi berguru kepada beliau-beliau tadi.
Masalah muncul saat saya kemudian bertanya, “sejak kapan anda menjadi muslim?”
Raut wajahnya berubah.
Demi menyaksikan perubahan mendadak itu saya tak ingat apakah ia kemudian segera berkata “inna lillahi wa inna ilaihi rojiun” atau “na’udzu billahi min dzalik.”
Saya terhenyak. Istri saya mengernyitkan dahi.
Ia memotong pertanyaan saya dengan perkataan “Mohon maaf, tolong biarkan saya menjabarkan masalah dari pertanyaan anda ini hingga selesai.”
Memotong pembicaraan orang lain adalah sesuatu yang tak lazim dilakukan disini, kecuali ada sesuatu yang tak biasanya.
Suasana disekitar kami mendadak hening padahal banyak orang lalu lalang, ditambah bising kereta datang dan pergi.
“Pertanyaanmu ini (menurut saya) didominasi oleh nafs (ia gunakan kosakata nafsu dalam bahasa Arab)”, ia melanjutkan.
Dalam beberapa detik pertama, saya mencerna pernyataannya. Hampir-hampir saya menolak untuk dihakimi seperti itu kalau saja saya tak sampai pada kesimpulan bahwa apa yang ia hakimkan kepada saya itu benar adanya.
Bahwa saya “kepo” dengan status keislamannya. Bahwa saya yang sudah Islam sejak kecil ini berhak bertanya kepada ia yang relatif “lebih baru”.
Tampaknya ia telah tersinggung dengan perkataan saya. Segera saya minta maaf.
Percakapan yang awalnya dilangsungkan dalam bahasa Jerman, saya segera rubah dalam bahasa Inggris agar saya dapat mengungkapkan perasaan saya dengan baik betapa saya menyesal dengan pertanyaan itu.
Ia kemudian menyitir sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “tidak ada seorang manusia yang terlahir kecuali dia terlahir atas fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.”
“Karenanya sepertinya aku cukup menjawab pertanyaanmu bahwa aku dahulu adalah ahlul fitrah”, tambahnya.
“Lagipula aku tak tahu apakah aku yang hari ini dapat menisbatkan diri sebagai seorang muslim. Dalam diriku, aku tahu persis, masih terdapat sebagian sifat-sifat jahil lagi kafir.”
“Dan aku selalu bangun setiap hari dengan pertanyaan apakah aku yang hari ini adalah seorang muslim?”, ia tak berhenti disitu.
“Bahkan aku tak tahu bila nanti aku dapat mati dalam kondisi mengucap kalimah laa ila ha illallaah.”
“Contohnya saja hari ini: seseorang telah menabrakku dari belakang (dengan sepeda). Mengakibatkan punggung dan perutku kram hingga harus ke rumah sakit. Bagaimana aku berani berangan-angan meninggal dengan kalimah laa ila ha illallah bila yang otomatis keluar dari mulutku saat ditabrak itu ialah keluhan rasa sakit, bukan asma-Nya?”
Jantung saya berdegup kencang. Jari-kemari kedua tangan saya reflek menekan-nekan botol minum yang sedari tadi saya pegang ke dada saya. Ujung mata saya basah.
Ia yang saya kira tersinggung dengan pertanyaan saya ternyata sama sekali tak tersinggung.
Ia telah memberikan kami pengajaran terpenting melalui redaksi-redaksi kalimatnya diatas, bahwa pertanyaan saya itu hanya sejauh mengurus keislaman orang lain tetapi melupakan keislaman diri saya sendiri.
Betapa ia benar. Kata-katanya menghujam deras. Hati saya menjerit.
Diatas kereta, istri dan saya sempat terdiam selama sekitar 10 menit pertama setelah kereta kami mulai berjalan. Kami masih berusaha mencerna.
Saya kemudian menyampaikan kepada istri saya bahwa pertemuan tersebut adalah kejadian yang tak bisa kita lewatkan begitu saja:
Bagaimana saya,
yang bangga sebab menjadi bagian umat Islam,
yang bacaannya hingga mutiara kebijaksanaan Ibnu Athoillah,
yang menisbatkan diri mengikuti ajaran Al-Ghazali,
ternyata justru telah melupakan urusan kafirnya diri.
Bagaimana saya,
yang sering berkeberatan apabila ada orang yang menghakimi orang lain dengan mudahnya,
pada akhirnya justru saya menghakiminya dengan sikap dan pertanyaan tadi kepadanya.
Bagaimana ia,
yang tak pernah kami kenal sebelumnya,
yang becakap-cakap hanya dalam waktu 5 menit bersama kami,
telah mengajarkan kepada kami,
bahwa disaat mayoritas orang-orang saling menghakimi satu sama lain,
ia adalah orang yang tak pernah lupa menghakimi dirinya sendiri.
Ia telah menelanjangi saya bulat-bulat; seluruh status, gelar, dan setiap buku yang saya pernah saya baca serta kebanggaan yang saya miliki seperti tak berarti sama sekali dihadapannya.
Saat kisah ini saya tulis, saya baru ingat bila sesaat sebelum acara di masjid dimulai tadi siang, beberapa jam sebelum diskusi kami dengannya di stasiun kereta ini, banyak hadirin melaksanakan sholat sunnah sebelum dhuhur termasuk dirinya.
Saat itu ia saya lihat memilih shaf paling belakang dan sholat dalam posisi duduk diatas kursi. Saya sempat menggumam dalam hati, “padahal ia masih berusia muda dan tampak baik-baik saja.”
Ya Rabb…
Syi’ir Tanpo Waton kemudian terngiang-ngiang dalam kepala saya, menemani hingga kami sampai di tujuan.
Artikel ini pertamakali ditulis di akun FB Muhammad Rodlin Billah
(Penulis adalah Ketua PCINU Jerman dan Mahasiswa program Doktor di Karlsruhe Institute of Technology peraih penghargaan Berthold-Leibinger Innovation Prize).